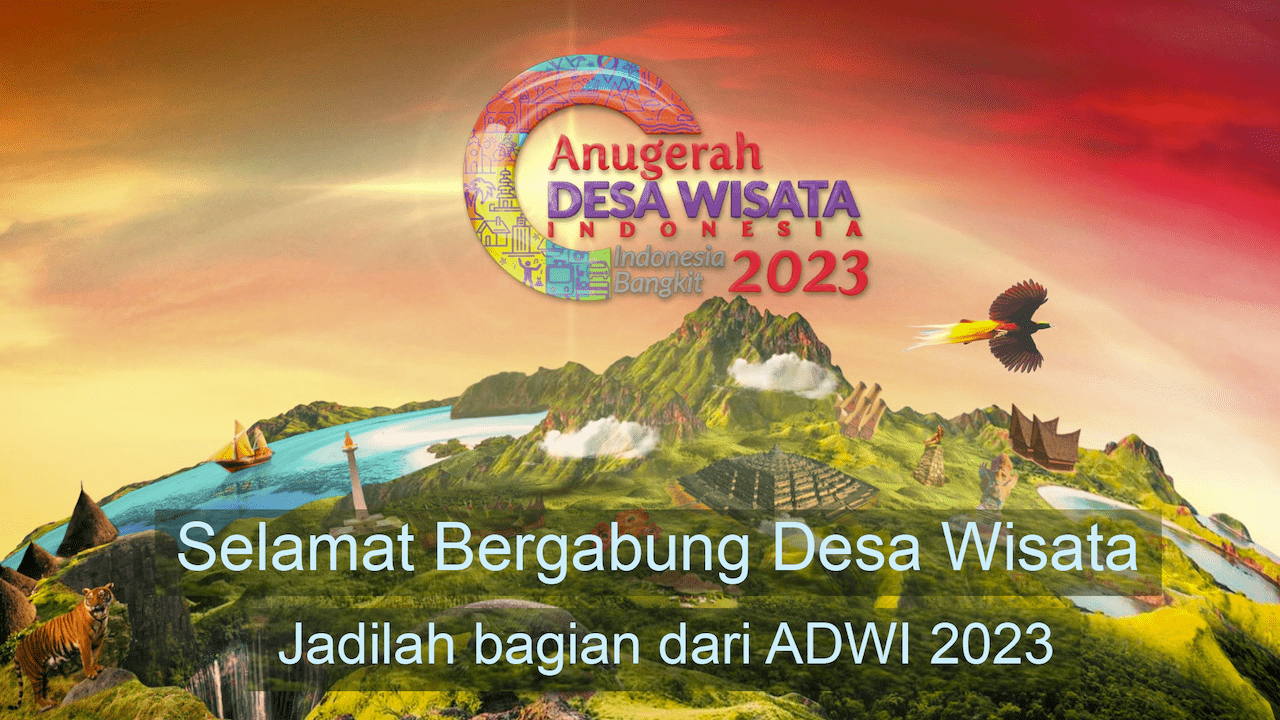Pada masa kesultanan Buton telah terjadi suatu peristiwa di mana masing-masing wilayah/kadie diminta untuk mengutus beberapa orang utusan yang mewakili wilayahnya masing-masing dengan maksud untuk menjadi laskar Buton pada peperangan melawan penjajah di wilayah Poleang. Pada saat itu utusan wilayah/kadie Wabula dalam hal ini diwakili oleh Ama Daidi, yang pada saat itu beliau terlambat tiba di Kesultanan Buton. Dengan demikian oleh Kesultanan Buton memberikan sanksi hukuman mati kepada Ama Daidi, karena beliau dinilai tidak kooperatif terhadap kesultanan Buton. Namun sanksi hukuman mati tersebut diringankan oleh Sultan karena alasan yang disampaikan oleh Ama Daidi cukup beralasan, sehingga Ama Daidi memohon agar hukuman yang diberikan kepadanya diperingan. Hal tersebut dikabulkan oleh Sultan Buton, maka hukuman mati diganti dengan duduk bersila selama ± 40 hari ditambah dengan membayar denda berupa uang sebanyak 100 Real.
Setelah masa hukuman 40 hari tersebut selesai dilaksanakan maka Ama Daidi berpikir agar bagaimana dapat membayar denda 100 Real. Maka beliaupun menghadap kepada Sultan Buton untuk membantu memberikan solusi bahwa bagaimana untuk melunasi yang 100 real, sementara kalau Ama Daidi kembali ke Wabula bagaimana mungkin mampu untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 real, dengan kondisi tanah di Wabula yang berbatu. Dengan penuh pertimbangan sosial dan kemanusiaan maka Sultan pun mmberikan solusi bahwa Ama Daidi harus menghadap ke Bonto Kumbewaha agar dapat diberikan lahan untuk bercocok tanam guna untuk melunasi denda tersebut. Maka Sultan Buton menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Bonto Kumbewaha untuk memberikan separuh lahan kepda Ama Daidi agar beliau dapat membayar denda yang dibebankan kepadanya. Maka Bonto Kumbewaha memberikan lahan dari sungai tondo sekarang batas Desa Walompo sampai Sangia Manuru yang sekarang Desa Manuru.
Disaat mendekati panen hasi pertanian yang melimpah yang terjadi saat itu adalah adanya gerombolan perampok yang nota bene pemburu rusa yang selalu mencuri hasil pertanian dan hasil ternak milik keluarga besar Ama Daidi, sehingga hal itu membuat resah keluarga Ama Daidi yang menjadikan Ama Daidi melaporkan kejadian tersebut kepada Sultan Buton. Mendengar itu Sultan Buton memerintahkan agar membunuh kelompok perampok tersebut seraya menyerahkan sebilah pedang dan sepucuk tombak sebagai senjata Ama Daidi, senjata tersebut masih diabadikan sampai saat ini.
Beberapa tahun kemudian denda sebanyak 100 real dapat dilunasi, berangsur-angsur keluarga dari Ama Daidi yang berdomisili di Wabula menyusul untuk berkebun bersama dengan Ama Daidi dan membentuk Kalimbo-limbo. Dari Kalimbo-limbo inilah mulai terbentuk komunitas masyarakat yang membentuk perkampungan, perkampungan tersebut diberi nama Kampung Matanauwe (Matanauwe artinya “Mata Air”) dengan dikepalai seorang kepala kampung yang dihjabat oleh Ama Ntokua ketika itu warga berjumlah ±150 KK.
Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan DI/TII yang menyebabkan terbakarnya kampung Matanauwe. Sehingga mengakibatkan warga mengungsi di Kecamatan Sampowajo (Sampolawa Pasarwajo). Warga kampung Matanauwe memilih Wakoko, Wasaga dan Dongkala sebagai daerah tujuan pengungsian untuk mengamankan dan menenangkan diri. Ujian tidak hanya berhenti disitu. Warga yang mengungsi di Wasaga mengalami cobaan. Mereka diserang wabah penyakit sehingga harus mengungsi lagi ketempat lain.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diadakan musyawarah di Wakoko Kecamatan Pasarwajo. Pertemuan diprakarsai oleh tokoh Matanauwe yang berada di Wakoko antara lain bernama La Pasere, La Kokoro, La Mole dan La Aihu untuk kembali ke Matanauwe. Setelah pertemuan ± 50 KK warga kembali ke Matanauwe. Rumah di Matanauwe belum permanen dan penduduk masih belum menetap dan masih tinggal di kebun. Situasi tersebut terjadi pada tahun 1964.
Pada tahun 1965, Desa Matanauwe definitif di bawah kepemimpinan Hanafi. Status Desa devinitif memberti ruang dan hak desa untuk megatur wilayahnya sendiri. Dikala itu Kepala Desa Hanafi memerintahkan agar rumah penduduk yang beratap alang-alang dibongkar dan dijadikan rumah panggung. Alasan kepala desa meminta warga desa memperbaiki rumah karena saat itu didukung kondisi hutan yang masih banyak pohon. Masyarakat tinggal mengambil kayu untuk dijadikan bahan bangunan. Dampaknya adalah desa menjadi lebih baik. Dampak buruknya dengan tidak melihat kesanggupan bagi KK janda karena mereka tidak mampu mengambil kayu di hutan. Untungnya masih ada masyarakat menerapkan sistem gotong royong untuk memperbaiki rumah. Hingga kini keadaan sosial budaya mulai punah secara perlahan.
Era tahun 70-an, Desa Matanauwe memiliki wilayah yang luas karena masih bergabung dengan Desa Walompo, Kuraa dan Sampuabalo yang masih berstatus dusun dengan jumlah KK mencapai 800 KK. Saat itu ada pembagian lahan oleh pemerintah bagi warga desa. Ada perbedaan pembagian antara KK laki-laki mendapat bagian 20 depa × 100 depa sedangkan KK perempuan hanya mendapatkan 15 depa × 100 depa. Kala itu masih ada budaya gotong royong di kalangan warga, melalui kesepakatan bagi kaum perempuan karena tidak sanggup membuat pagar maka pagarnya dibuatkan oleh laki-laki yang berdekatan lahannya dengan kesepakatan bahwa kaum perempuan membersihkan kebun bagi kaum KK laki-laki yang membantu membuat pagarnya. Perbedaan tersebut karena faktor tenaga perempuan yang dianggap lemah. Dengan adanya pembagian lahan, maka masyarakat mulai fokus berkebun sehingga mulai tersedia bahan makanan berupa jagung, ubi dan sayur-sayuran yang sudah mulai dirasakan maka didirikanlah sekolah dasar secara swadaya masyarakat. Kepala Desa pada era 70-an adalah Hanafi.
Era tahun 80-an, masuknya proyek pemerintah yakni perintisan jalan poros Lasalimu, pengerasan dan pengaspalan jalan desa. Proyek tersebut menyebabkan akses jalan ke Desa lain dan ibu kota kecamatan dan kota bau-bau semakin lancar. Saat itu pula mulai didirikan SMP Filial Pasarwajo. Bersamaan dengan itu terjadi pengungsi dari Suku Cia-Cia Laporo.
Era tahun 90-an, dibangun perpipaan sarana air bersih terbatas untuk setiap RT terdapat 2 hidran umum. Disamping itu ada pembangunan infrastruktur seperti rumah jabatan Kepala Desa, gedung serba guna, Puskesmas Siotapina, penambahan perpipaan sarana air bersih dan WC umum. Pelayanan asyarakat desa Matanauwe menjadi lebih baik.
Era 2000-an, pembangunan terus dilakukan seperti penambahan perpipaan sarana air bersih, pembangunan sekolah SMAN-1 Siotapina, pembangunan jalan setapak ke dusun Bajo sepanjang 500 meter dan pembagian raskin bagi warga serta pemekaran dusun Bajo menjadi Desa Bahari Makmur pada tahun 2011.
Fasilitas
- Areal Parkir
- Cafetaria
- Kamar Mandi Umum
- Musholla
- Selfie Area
- Spot Foto
Video
Atraksi Wisata
Belum ada atraksi
Kamar Homestay
Belum ada homestay